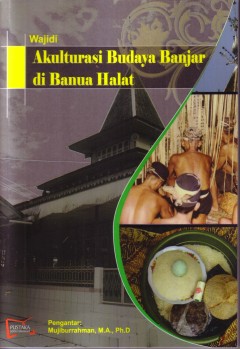Jerat Pasal Karet Masa Kolonial Belanda
Oleh Wajidi
Sembilan Pasal dalam UU ITE (Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) kini diperdebatkan untuk kembali direvisi karena mengandung pasal karet. Adanya pasal karet itulah yang sejauh ini telah menjerat 94 orang karena antara lain akibat komentar di media sosial. Alih-alih untuk mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, pasal karet dalam UU ITE ditengarai telah menjadi senjata para pihak yang anti kritik, membungkam para pihak yang berseberangan, dan yang paling prinsif adalah mengebiri kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Ada yang merasa takut mengeluarkan kritik kepada pemerintah karena kuatir dipolisikan, takut distigma radikal, menyebar ujaran kebencian, dilaporkan dan ujung-ujungnya dipenjara. Tak tanggung-tanggung, tokoh sekaliber ekonom Kwik Kian Gie mengungkapkan kegundahannya: “saya belum pernah setakut saat ini mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif”. Atau Prof. Salim Said yang mengaku kerap menahan diri bicara karena takut. Bapak Presiden Joko Widodo merespon kegundahan banyak pihak dengan mengajak DPR untuk merevisi kembali UU ITE.
Diksi Kolonial
Pasal karet merupakan diksi kaum pergerakan untuk pasal multitafsir dalam KUHP (Wetboek van Strafrecht) masa Hindia Belanda. Disebut “pasal karet” karena beberapa pasal dalam KUHP itu mempunyai konotasi arti dari perkataan-perkataan yang dipergunakan tidak mengandung makna pasti tetapi bersifat elastis sehingga dapat diterapkan sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh penguasa guna mengatasi pelbagai kasus yang merugikan atau mengancam sistem kolonial Pasal-pasal dimaksud diantaranya: Pasal 153 bis; Pasal 153 ter; Pasal 161 bis; dan Pasal 171 bis.
KUHP Hindia Belanda memberikan ancaman hukuman yang cukup berat terhadap penyiaran kata-kata, surat, gambar, secara langsung atau tidak langsung, secara terbuka atau sembunyi-sembunyi, gagasan yang bertujuan mengacaukan ketertiban dan ketenteraman dan mendesak kejatuhan pemerintah Hindia Belanda, atau secara terang-terangan melahirkan rasa permusuhan, kebencian, atau kritik terhadap pemerintah. Pasal-pasal karet menjadi amunisi Pemerintah Hindia Belanda untuk menindak perkumpulan yang asas tujuannya dirahasiakan, begitupula perkumpulan yang bermaksud hendak merobohkan pemerintah (gezag) atau yang bermaksud mengganggu ketenteraman hidup masyarakat. Agar tidak terkena persdelic dan delik bicara, para aktivis pergerakan mesti hati-hati memuat tulisan dan dalam menyelenggarakan rapat seperti Rapat Terbuka (openbaar vergadering), “Rapat Di bawah Langit” (openlucht vergadering), dan Rapat Tertutup (besloten vergadering). Mereka harus mengikuti aturan, dan pastinya polisi PID (Politieke Inlichtingen Dienst) senantiasa hadir untuk memantau gerak-gerik dan pembicaraan.
KUHP ini dilengkapi dengan Ordonansi Pers (Persbreidel Ordonantie) tahun 1931 dan Ordonansi Pengawasan Pers tahun 1937 yang berisi kekuasaan mutlak kepada pemerintah untuk menutup sementara waktu penerbitan surat kabar, tanpa proses hukum, demi tegaknya hukum dan ketertiban. Sementara terhadap pegawai negeri (ambtenaar), Gubernur Jenderal mengeluarkan Muilkorf-Circulaire atau Sirkuler-Pemberangusan yakni surat edaran Gubernur Jenderal bertanggal 27 September 1919 yang berisi larangan bagi pegawai pemerintah untuk mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis yang dapat merongrong kekuasaan pemerintah.
Pasal-Pasal 153 bis berbunyi: “Barang siapa dengan perkataan, tulisan atau gambar melahirkan pikirannya yang biarpun secara menyindir atau samar-samar, memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum atau menentang kekuasaan Pemerintah Nederland atau Pemerintah Hindia Belanda dapat dihukum penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimum Rp 300,00”. Perkataan-perkataan yang bersifat karet pada pasal itu, yaitu ‘menyindir’, ‘samar-samar’ dan ‘mengganggu keamanan umum’.
Pasal 153 bis sifat karetnya sama dengan isi pasal 153 ter yang berbunyi: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang memuat pikiran seperti dimaksud dalam pasal 153 bis dapat dihukum penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 300,00”. Pasal 153 ter, seringkali khusus ditujukan pada para penanggungjawab media massa (termasuk redaktur) yang tidak menyebutkan nama penulis atau samaran.
SK Pantjaran Berita 4 Agustus 1936 mengungkapkan, bahwa di dalam Volksraad (Dewan Rakyat), Pasal 153 bis dan ter ini seringkali didebat para anggota dewan yang pro pergerakan, namun pemerintah tetap bergeming. Mereka mengatakan, artikel tersebut sangat merugikan karena terlalu bersifat karet, mengkritik cara pemeriksaan, dan penahanan yang lama karena alasan yang dibuat-buat. Berdasar data statistik di Departement van Justititie, kalau sudah dinyatakan terjerat pasal karet tidak ada satu persen pun yang lepas dari pasal karet itu. Tak jarang wartawan yang yang ditahan karena melanggar pasal 153 bis dan ter mengalami kekerasan fisik.
Korban Pasal Karet
Kaum pergerakan di Kalimantan Selatan tidak luput dari jeratan pasal karet. DiantaranyaH. Ahmad Darmawi, tokoh Parindra cabang Kandangan. Ia dijerat pasal karet lantaran sering menulis artikel yang bersifat politik melalui Mingguan Pembangunan Semangat. Ia dituduh persdelict dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun oleh Landraad Kandangan. Upaya Mr. Rusbandi, selaku Komisaris Daerah Parindra dan pembela tidak berhasil meyakinkan hakim kolonial, sehingga H. Ahmad Barmawi dikirim ke penjara Sukamiskin di Jawa Barat.
Pasal karet juga menjerat para pimpinan Parindra cabang Amuntai karena mereka membuat mosi menentang peraturan Heeren Dienst (erakan, rodi atau kerja paksa) atas penduduk lelaki berusia 45 tahun ke atas. Pemenjaraan itu telah memunculkan demonstasi (openlucht vergadering) yang diikuti ribuan orang ke kantor Kontrolir Amuntai untuk menuntut pembebasan rekan mereka. Namun oleh Pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai usaha untuk memberontak. Pimpinan demontrasi H. Amir, Edwar Sandan, H. Morhan, H. Seman, dan Abdulhamidhan diseret ke pengadilan dengan tangan dirantai. H. Morhan ditangkap di Surabaya kemudian dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, dan bersama Abdulhamidhan yang divonis 1 tahun dikerjapaksakan di Penjara Ampah (Kalimantan Tengah), sedangkan H. Amir dan Edwar Sandan masing-masing dikenakan penjara 2 tahun dan dikirim ke penjara Sukamiskin, Jawa Barat.
Keluarga Edwar Sandan paling menderita di balik peristiwa itu. Ketika mendengar Edwar Sandan akan dikirim ke penjara Sukamiskin, isterinya yang mengandung tua menyusul ke Banjarmasin menumpang kapal sungai. Setelah kembali ke rumahnya di Tangga Ulin, isterinya itu meninggal dunia setelah melahirkan anaknya. Karena penderitaan hidup yang tak tertahankan tanpa memiliki kedua orang tua, maka puteri sulungnya menderita sakit jiwa sehingga tidak dapat meneruskan merawat adik-adiknya yang masih kecil itu. Sementara itu, diberitakan pula Edwar Sandan meninggal dunia dalam masa menjalani hukumannya di Penjara Sukamiskin, Jawa Barat.
Nasib serupa juga dialami oleh Hadhariyah M, Ketua Cabang Parindra Banjarmasin yang oleh Belanda telah dicap sebagai seorang “Hollander Hater” (Pembenci Belanda) dalam tulisan-tulisan politiknya. Beliau telah menjadi korban delik bicara dalam suatu rapat umum Parindra di Barabai dengan tuntutan melanggar pasal 151 bis. Hadhariyah membahas bahwa belanja hidup seekor anjing yang ditangkap dan dikurung oleh polisi Belanda di Surabaya karena tanpa penning adalah sebesar f. 50 sehari yang kelak harus dibayar oleh sang punya anjing itu. Sedangkan belanja hidup seorang rakyat Indonesia, cukup sebenggol atau 2,5 sen sehari. Bayangkan kata Hadhariyah M, betapa ambruk martabat hidup dan betapa miskinnya rakyat Indonesia di Hindia Belanda. Di tanah airnya sendiri. Karena ucapannya itu, maka ditangkaplah Hadhariyah M dan diganjar hukuman penjara selama 3 bulan dan membayar denda f. 100.
Lebih lanjut Hadhariyah M menceritakan bahwa pada saat beliau M ingin berangkat ke Surabaya untuk menghadiri Konferensi Besar Parindra di Surabaya, maka pada tanggal 17 Juni 1941 dalam kesibukan persiapan keberangkatan, beliau ditangkap dan didakwa melanggar pasal-pasal 156, 157, dan 193 bis. Pelanggaran itu terjadi, karena Hadhariyah M telah menulis sebuah roman politik yang berjudul “Suasana Kalimantan” dan diterbitkan di Medan dengan judul “Tersungkur Di Bawah Kaki Ibu”. Tulisan itu dianggap pemerintah bertendensi politik , melakukan persdelict, sehingga dijatuhi vonis 4 tahun penjara.
Setali tiga uang dengan Hadhariyah M, jeratan pasal karet juga dirasakan seorang ambtenaar bernama H. Ali Baderun yang juga Ketua Parindra cabang Barabai. Ia megalami delik bicara pada Parindra tahun 1939. Ia ditangkap dan oleh Landraad Kandangan yang bersidang di Barabai, H. Ali Baderun dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, meski sudah berupaya mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak hanya itu, jabatan H. Ali Baderun dalam pemerintahan sipil dicabut dan sesudah itu beliau diberhentikan sama sekali sebagai pegawai negeri sipil.
Salah seorang wartawan yang pernah mengalami persdelict adalah A.A. Hamidhan. Selama hidupnya A.A. Hamidhan pernah mengalami tiga kali masuk penjara karena Persdelict, yakni Strafgevangenis Cipinang (dahulu Meester Cornelis) di Jatinegara selama 2 bulan karena persdelict waktu bekerja di surat kabar Bendahara Borneo di Samarinda (1930), penjara Banjarmasin (kini Gedung Pos Besar Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat) selama 6 minggu karena Persdelict Soeara Kalimantan (1932), kemudian di tahun 1936 masuk lagi selama 6 bulan di penjara Banjarmasin.
Wartawan Aam Niu dalam Majalah Dwikala ARENA Medan No. 2 Tahun IV Februari 1948 memuat kisah Yusni Antemas wartawan Terompet Rakyat. Beliau yang oleh Belanda diberikan julukan “Ektremis Berbulu Wartawan”, karena selain anggota Gerpindom beliau adalah juga wartawan Terompet Rakyat yang dengan tulisan-tulisannya yang tajam terasa memekakkan telinga pemerintah NICA-Belanda. Akibatnya beliau dipanggil dan diminta untuk menghentikan kegiatannya sebagai wartawan. Iming-iming fasilitas dari Pemerintah Belanda agar bersedia menghentikan penerbitan harian Terompet Rakyat beliau tolak sehingga berakibat kepada pemukulan yang dilakukan oleh militer Belanda terhadap Yusni Antemas. * Tulisan ini terbit di SK Banjarmasin Post, Rabu 3 Maret 2021 dengan judul “Pasal Karet di Masa Kolonial Belanda”.