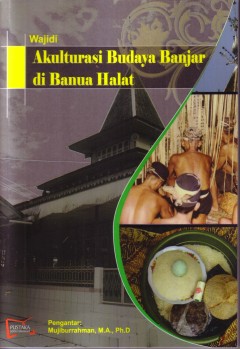TAJUN DAN MADAM Dalam Migrasi Orang Banjar ke Perantauan
Oleh Wajidi
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi satu fenomena yang menarik yang tidak pernah lagi terjadi pada masa kini, yakni migrasi besar-besaran orang Banjar keluar Kalimantan Selatan (Kalsel) menuju berbagai tempat di kepulauan di Nusantara. Secara umum migrasi atau merantau dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai madam dalam bahasa Banjar yang artinya pergi merantau dalam waktu yang lama meninggalkan banua (kampung halaman). Namun ada istilah lain yang disebut Tajun. Tanah rantau tempat tujuan mereka madam disebut “pamadaman” yang artinya sama dengan “Perantauan”. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan: (1) pengertian Tajun dan Madam dalam konteks migrasi orang Banjar di Kalimantan Selatan; (2) latar belakang dan kasus terjadinya tajun dan madam dalam konteks sejarah migrasi orang Banjar di Kalimantan Selatan ke perantauan.
Makna Tajun dan Madam
Ada dua pola migrasi yang dilakukan oleh orang Banjar dahulu, yakni madam dan tajun. Dalam konteks ini, maka pengertian madam dikonotasikan sebagai pergi merantau yang dilakukan secara sadar, misalnya untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Keberangkatan mereka dari rumah dianalogikan keluar dari pintu depan, dilepas oleh keluarga, kerabat dan jiran. Sebaliknya, tajun adalah migrasi yang dilakukan oleh orang Banjar yang dilakukan secara sadar namun terpaksa karena berbagai alasan yang sifatnya negatif, misalnya karena adanya perkelahian di kampung, malu karena bercerai, atau pada kasus masa perang Banjar dahulu adalah para pejuang yang melarikan diri agar tidak ditangkap oleh militer Belanda. Orang yang tajun meninggalkan kampung halaman dianalogikan sebagai keluar diam-diam melewati pintu belakang rumah, jika pun ada yang mengetahui hanya keluarga terdekatnya saja.

Mohamed Salleh Lamry (1997: 1) menulis bahwa mulai awal abad ke-20, migrasi dari Indonesia berlaku secara besar-besaran dalam konteks ekonomi kolonial yang memerlukan tenaga kerja yang ramai di Malaysia. Sebagian mereka menjadi kuli kontrak di estate-estate pemodal Inggris. Akan tetapi, lebih ramai orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandailing, Kampar, dan lain-lain yang datang ke Malaysia untuk membuka sawah padi, atau kebun kelapa, dan kemudian kebun getah (karet). Lebih lanjut Mohamed Salleh Lamry mengatakan bahwa pada hakikatnya sebagian besar orang Melayu di beberapa negeri di Malaysia, seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Johor kini adalah terdiri dari keturunan pendatang dari Indonesia.
Sebagian besar mereka itu tidak pernah pulang kembali ke Kalsel. Mereka membuka lahan dan mendirikan kampung Banjar yang semua penduduknya adalah orang Banjar atau menjadi komunitas kecil di tengah-tengah perkampungan etnis lain di berbagai belahan wilayah kepulauan Nusantara, baik yang kini berada dalam wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand Selatan dan Philipina Selatan, dan negara lainnya dikenal sebagai masyarakat Banjar serantau.
Sebagian dari mereka ada yang masih bisa menjalin komunikasi dengan kerabatnya di Kalsel, karena kerabatnya di banua masih dikenali. Namun tidak sedikit pula yang putus sama sekali karena yang mereka ketahui hanyalah padatuan mereka berasal dari Kalsel, sedangkan berasal dari daerah mana dan dimana kerabat padatuan atau moyang mereka berada, mereka tidak lagi mengetahuinya.
Latar Belakang Migrasi
Fenomena migrasi (madam dan tajun) yang dilakukan orang Banjar merupakan pola umum yang juga dilakukan oleh berbagai etnis di Nusantara di di akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Migrasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor kondisi politik, ekonomi, keamanan, atau faktor tidak kondusifnya daerah asal mereka.
Faktor ekonomi seperti untuk mencari penghidupan yang lebih baik merupakan salah satu alasan mereka bermigrasi, misalnya yang dilakukan orang Banjar ketika bermigrasi ke Semenanjung Malaya sebagai buruh penyadap karet. Penyadapan getah karet dan perluasan lahan perkebunan karet tentu saja memerlukan tenaga kerja atau buruh harian. Dan tenaga itu didatangkan atau diperoleh dari orang-orang yang datang ke Semenanjung Malaya.
Orang-orang Banjar tidak segan bekerja di tempat yang jauh dari kampungnya. Walaupun mereka akan segera kembali jika telah mendapat banyak uang atau keadaan di perantauan tidak menguntungkan lagi. Seperti ketika perkebunan tembakau Deli baru dibuka, banyak orang Banjar pergi kesana untuk membuka lahan dan membuat bangunan (L. Potter dalam Tundjung, 2008: 6).
Diantara yang melakukan madam adalah sebuah keluarga dari Barabai ke Batu Pahat, Malaysia. Cerita bermula ketika pada tahun 1920-an Itit, isteri dan anaknya Suri bersama Kumbih berangkat madam dari desa Awang Barabai dengan tujuan Batu Pahat, Johor di Semenanjung Malaya atau Tanah Melayu (kini Semenanjung Malaysia).
Tujuan mereka madam ke Batu Pahat adalah untuk mengadu nasib peruntungan sebagai buruh penyadab karet. Pada saat itu, karet telah menjadi primadona ekspor di Semenanjung Malaya. Perkebunan karet terus diperluas dan permintaan dunia relatif tinggi sehingga harga jualnya pun bagus. Penyadapan getah karet dan perluasan lahan perkebunan karet tentu saja memerlukan tenaga kerja atau buruh harian. Dan tenaga itu didatangkan atau diperoleh dari orang-orang yang datang ke Semenanjung Malaya.
Di Kalimantan Selatan, tanaman karet mulai diperkenalkan oleh pengusaha Belanda maupun orang-orang Banjar yang baru pulang dari Semenanjung Malaya atau dibawa oleh orang Banjar yang kembali dari tanah suci Mekkah kemudian singgah di sana. Di onderafdeling Kandangan, kebun karet yang tertua dapat dijumpai di kampung Luhgawang (Longawang), ketika tahun 1912 Haji M. Saleh membawa bibit dari perkebunan karet Batu Pahat, Johor. Penduduk di sana juga mendatangkan banyak bibit dari daerah Penang (Tundjung, 2008: 8).
Suatu ketika, Itit kembali pulang ke banua. Konon kabarnya terjadi perceraian dengan isterinya di Batu Pahat, sehingga ia hanya datang sendirian di desa Awang. Sedangkan Suri atau Isur beserta ibunya dan Kumbih bertahan di Batu Pahat. Beberapa waktu kemudian, Itit menikah lagi dan kemudian menghasilkan keturunan sebanyak empat orang.
Meski terpisah jauh, kontak antara Itit dengan Suri bin Itit dengan alamat surat di “Muka Pasar 5 Batu Pahat, Johor Malaysia” terus terjalin. Tidak hanya antara ayah dan anak, namun juga antara ke empat anak Itit di banua dengan Suri di Batu Pahat yang konon kabarnya telah mempunyai keturunan sebanyak delapan orang hasil pernikahannya dengan dengan seorang perempuan bernama Siti asal Pandahan Rantau yang di tahun 1925 dibawa ayah ibunya madam ke semenanjung Malaya.
Berkaitan dengan cerita madamnya Itit dan keluarga ke Semenanjung Malaya, mereka hanyalah segelintir dari ribuan orang Banjar yang sejak akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 pergi merantau ke berbagai kepulauan di Nusantara. Sebagian besar mereka itu tidak pernah pulang kembali ke Kalsel. Mereka membuka lahan dan mendirikan kampung Banjar yang semua penduduknya adalah orang Banjar atau menjadi komunitas kecil di tengah-tengah perkampungan etnis lain di berbagai belahan wilayah kepulauan Nusantara, baik yang kini berada dalam wilayah NKRI seperti Sapat dan Tembilahan (Indragiri Hilir Provinsi Riau), Bintan (Provinsi Kepulauan Riau), Kuala Tungkal (Provinsi Jambi), Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Asahan (Provinsi Sumatera Utara), Kaltim, Kalteng, Kalbar, pulau Jawa, pulau Lombok dan Bima (Nusa Tenggara Barat), Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar, dan Maluku (Ambon dan pulau Key), dan lain sebagainya. Atau di daerah-daerah yang menjadi bagian negara Malaysia, seperti Kerian-Parit Buntar-Sungai Manik-Sabak Bernam di Perak, Sungai Besar-Tanjung Karang-Bagan Datoh di Selangor, Batu Pahat di Johor, dan Sabah, dan juga di negara Brunei Darussalam, Singapura, dan Pattani Thailand. Mereka bermukim dan berusaha di tempat baru serta beranak bercucu hingga sampai ke generasi ke empat atau ke kelima.
Menurut Sartono Kartodirdjo (1975: 116-118), fenomena migrasi bukanlah semata-mata faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan mereka, namun dikarenakan oleh faktor lain seperti faktor politik yang kadang-kadang membuat orang menentukan harus pindah ke daerah lain. Bambang Purwanto dalam A. Muthalib (2008:24) menyatakan bahwa ketika tekanan politik Belanda terhadap Banjarmasin dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan semakin intensif, orang Bugis dan Banjar semakin banyak yang membuka daerah rawa-rawa di sepanjang pantai timur Sumatera.

Terkait dengan latar belakang migrasi orang Banjar, maka selain bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik (faktor ekonomi), juga untuk menghindar dari penindasan Pemerintah Hindia Belanda (faktor politik dan keamanan). Faktor inilah yang menyebabkan yang menyebabkan banyak orang Banjar yang tajun, terutama pada masa Perang Banjar (1859-1906). Misalnya, banyak keturunan orang Banjar Kelua dan Alai (Barabai), dan Kandangan yang bermukim di Malaysia yang ditengarai adalah keturunan pejuang Perang Banjar, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya peninggalan berupa pedang, parang, wafak, atau surat berharga yang mereka nyatakan diwarisi dari nenek moyang mereka yang dahulunya melarikan diri ke semenanjung Malaysia untuk menghindari kejaran aparat kolonial Belanda.
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kresidenan Borneo Selatan (Kalimantan Selatan) di tahun 1920 an turut mendorong terjadinya migrasi orang Banjar. Kondisi itu terkait dengan dampak ekonomi dunia yang tengah dilanda malaise. Selain itu, adanya perlakuan diskriminasi Pemerintah Hindia Belanda terhadap pribumi mengakibatkan kehidupan masyarakat Banjar di bawah penguasaan Belanda juga sangat memprihatinkan.
Orang Belanda (termasuk orang Eropa lainnya) sebagai kelas tertinggi, memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Pembangunan seperti di bidang pendidikan, tempat rekreasi, perumahan, bioskop, dan fasilitas penting lainnya adalah untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dan orang-orang Eropa. Hanya orang kulit putih atau yang dipersamakan yang boleh memasuki fasilitas penting tersebut, sedangkan Bumiputera adakalanya dilarang masuk karena ada tanda-tanda tertentu bertulisan larangan, seperti: “Verboden toegang voor Inlanders en Honden (dilarang masuk untuk orang bumiputera dan anjing” (Saleh, 1981-1982: 37).
Perlakuan diskriminasi sebenarnya tidak hanya dikenakan antara golongan pribumi dengan orang Eropa atau Timur Asing, melainkan juga antara golongan pribumi muslim dengan pribumi penganut agama Kristen. Pada tahun 1920-an, guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal dan kaum masjid dikenakan kewajiban oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan Ordonnantie Heeren Dienst yang menyangkut erakan atau kerja rodi, sedangkan guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending justru dibebaskan dari kewajiban itu.
Diskriminasi atau pengklasifikasian status sosial yang terjadi di dalam masyarakat mengundang pertentangan sosial dan ini menyebabkan seringnya terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah. Diskriminasi dan penindasan seperti itulah yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat bumiputera.
Terhadap pribumi pemerintah Hindia Belanda mengenakan berbagai pungutan seperti Pajak Pencaharian, Pajak Tanah, Pajak Kepala, Pajak Erakan (uang kepala), Bea Masuk, Pajak Penyembelihan dan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi. Selain itu, setiap orang, kecuali golongan pangreh praja, yang berumur antara 18-45 tahun dapat dikenakan kerja rodi (kerja erakan) yang sangat memberatkan rakyat yang kesemuanya untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.
Kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan rodi dan berbagai pajak dan pungutan, dampak depresi ekonomi dunia saat itu, dan ditambah dengan pendidikan yang kurang maju menjadi dominan sifatnya antara tahun 1900 –1928 di Kalimantan Selatan. Kondisi demikian mengakibatkan keresahan yang bermuara kepada munculnya pemberontakan Guru Sanusi 1914-1918 dan pemberontakan Gusti Darmawi tahun 1927. Keadaan itu pula yang mengakibatkan banyak penduduk khususnya dari Hulu Sungai yang melakukan eksodus ke pesisir Timur Sumatera seperti Kuala Tungkal, Sapat, Tembilahan. Sampai tahun 1950 jumlah penduduk suku Banjar di daerah Sapat dan Tembilahan mencapai 250.000 orang (Saleh et al,1978/1979: 51).
Sumatera Utara merupakan salah satu daerah pamadaman yang cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ahmad Fauzi (2010:2) diperkirakan orang Banjar di Sumatera Utara saat ini berjumlah lebih kurang 180.000 orang dengan perincian kab. Langkat 70.000 orang, Deli Serdang 30.000 orang, Serdang Bedagai 50.000 orang, Asahan 20.000 orang, kabupaten/kota lainnya kurang lebih 10.000 orang.
Informasi lain sebagaimana disebutkan A. Muthalib (2008:26) bahwa orang Banjar yang telah bermukim di Indragiri Hilir pada tahun 1900 sekitar seribu jiwa. Lima belas tahun kemudian (1915) jumlah mereka meningkat drastis, yakni 18.798 jiwa. Pada akhir perang Dunia I atau dekade kedua abad ke-20, jumlah mereka diperkirakan 20 ribu jiwa. Selain ke pesisir Sumatera, puluhan ribu penduduk Hulu Sungai juga pergi untuk menetap di Melaka (Sjamsuddin, 2001: 9). Mungkin yang dimaksud Sjamsuddin di Malaya, bukan di Melaka. Kalau di Melaka tidak ada orang Banjar seramai itu, kerana Melaka bukan tumpuan migrasi orang Banjar.
Menurut Tunku Shamsul Bahrin (1964) sebagaimana dikutip dari Mohamed Salleh Lamry (2010:4) bahwa berdasarkan sensus penduduk Semenanjung Malaya tahun 1911, orang Banjar di Malaya pada masa itu berjumlah 21.227 orang. Umumnya mereka bermukim di Perak, Selangor dan Johor. Pada tahun 1921 orang Banjar di Malaya meningkat hampir 80% menjadi 37.484 orang. Antara tahun 1921 hingga 1931 penduduk Banjar di Malaya bertambah 7.503 orang menjadi 45.351 orang. Perak, Johor dan Selangor masih merupakan negeri di mana jumlah orang Banjar paling ramai. Dalam tiga negeri inilah tinggal 96% orang Banjar di Malaya.
Menurut sensus tahun 1930 di Semenanjung Malaya terdapat 45.382 orang Banjar dan pada tahun 1947 angka ini meningkat ke angka 62.356 orang (Dzul Karnain Asnawi, 2010: 6). Sedangkan menurut sensus di Malaya tahun 1931, orang Banjar kelahiran Hulusungai mencapai 45.433 jiwa. Sedangkan di Sumatera pada tahun yang sama 77.838 jiwa; tersebar di Riau, Jambi, Medan, dan pesisir utara lainnya (Arbain, 2009:235).
Proses migrasi besar-besar orang Banjar memang sudah terjadi pada abad ke-18 ketika Belanda melakukan campur tangan dalam perebutan tahta antara Pangeran Nata dan Pangeran Amir yang berujung kepada kekalahan Pangeran Amir dan akhirnya dibuang ke Ceylon (Sri Langka). Untuk menghindari dari penangkapan dan hukuman dari pihak kolonial Belanda, maka pengikut Pangeran Amir melakukan eksodus ke berbagai tempat yang dirasa aman. Migrasi orang Banjar keluar Kalsel semakin banyak ketika terjadinya Perang Banjar yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun (1859-1906). Dan migrasi itu mencapai puncaknya pada dekade-dekade pertama abad ke-20, disaat Pemerintah Hindia Belanda telah semakin intens menancapkan kekuasaan dan menjalankan pemerintahan kolonial yang diskriminatif dan menindas kaum pribumi.
Catatan kependudukan tahun 1930 menunjukkan jumlah keseluruhan penduduk Banua Lima atau Hulusungai melebihi angka 500.000 jiwa. Dari rasio jenis kelamin yang berjumlah 91-92 laki-laki per 100 perempuan, menunjukkan bahwa laki-laki Banjar banyak meninggalkan kampung halaman (Potter, 2001: 401).
Migrasi orang Banjar ke berbagai tempat di kepulauan Nusantara juga didukung budaya madam, setidaknya budaya madam yang dimiliki oleh orang Alabio untuk berdagang keluar kampung halaman (Rambe dalam Taufik Arbain, 2009: 6). Selain subetnis Alabio, orang Negara, Kelua, dan Amuntai dikenal sebagai pedagang handal yang berjualan ke berbagai tempat.
Migrasi orang Banjar didukung oleh penguasaan teknologi pembuatan perahu (jukung) dalam berbagai bentuk dan jenis keperluan untuk transportasi sungai, pantai dan lautan. Kemampuan itu dengan sendirinya menjadikan orang Banjar memiliki tradisi berlayar baik sebagai pelaut, nelayan, dan pedagang antar pulau (interensuler). Tak mengherankan jika pada masa Kerajaan Negara Dipa, Negara Daha, dan Kesultanan Banjar, jung-jung yang dibawa pedagang Banjar banyak berlabuh di berbagai bandar di pantai utara pulau Jawa.

Ketika Islam berkembang pesat di Kesultanan Banjar yang mengharuskan penganutnya untuk melakukan perjalanan haji ke Mekkah bagi yang mampu, maka kemampuan orang Banjar berlayar mengarungi samudera semakin terasah. Adalah hal biasa jika orang Banjar melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekkah dengan menaiki kapal layar sendiri pulang pergi selama setahun lamanya. Kemampuan memiliki, menguasai teknologi perkapalan dan adanya tradisi berlayar dan berdagang antar pulau dengan perahu tradisional itulah yang menjadikan orang Banjar memiliki mobilitas tinggi, berlayar dari satu pulau ke pulau lain dan menyusuri sungai hingga jauh ke pedalaman untuk mencari tempat bermukim. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menumpang kapal uap milik maskapai Belanda yang hanya merapat di bandar besar saja.
Putusnya komunikasi antara orang Banjar banua dengan perantauan barangkali disebabkan karena semakin berkurangnya armada perahu-perahu tradisional Banjar yang melayari lautan karena semua kegiatan perdagangan diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda, seiring dengan berhentinya perlawanan orang Banjar di awal abad ke-20 dan monopoli perdagangan Cina. Berbagai upaya untuk melawan pengaturan Belanda itu dan monopoli pedagang Cina, seperti yang dilakukan organisasasi Sarekat Islam cabang Banjarmasin dengan mendirikan Sarekat Pelayaran sebagai upaya untuk memperlancar transportasi sungai yang merupakan jalur perdagangan penting di Kalimantan Selatan, namun agaknya usaha-usaha itu tidak mampu melawan monopoli perdagangan yang telah lama dikuasai orang-orang Cina yang telah lama mendapat perlakuan istimewa yang diterimanya dari pemerintah, di samping eksploitasi pemerintah kolonial sendiri di bidang ekonomi (Wajidi, 2007: 123).
Dengan semakin sedikitnya perahu-perahu Banjar yang melayari lautan, maka semakin jarang orang Banjar di perantauan atau sebaliknya untuk saling berkunjung. Akibatnya untuk waktu sekarang masing-masing pihak mengalami kesulitan untuk menelusuri kembali sanak keluarga keluarganya. Sebagian dari mereka ada yang masih bisa menjalin komunikasi dengan kerabatnya di Kalsel, karena kerabatnya di banua masih dikenali.
Kini dengan semakin terjangkaunya biaya penerbangan pesawat, maka semakin ramai kedua belah pihak warga Banjar dari dua negara yang berbeda yang masih menjalin komunikasi saling melakukan kunjungan silaturahim untuk merekatkan dan mengakrabkan kembali hubungan kekeluargaan mereka, atau datang ke Banjarmasin untuk sekedar mengetahui kampung halaman moyang mereka atau mencoba peruntungan untuk menelusuri keturunan kerabat mereka di banua dengan bekal alamat atau susur galur seadanya. Sebagian kerabat yang dicari ditemukan atau terjalin kembali, namun tidak sedikit pula yang putus sama sekali karena yang mereka ketahui hanyalah padatuan mereka berasal dari Kalsel (seperti dari Barabai, Kandangan, Alabio, Nagara, Amuntai, Kelua), namun dimana atau di kampung apa padatuan mereka dahulunya berada mereka tidak mengetahuinya.